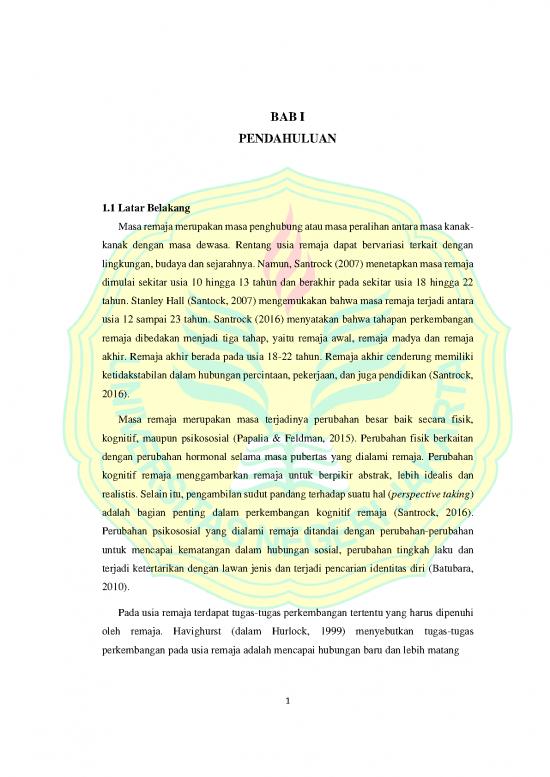Authentication
459x Tipe PDF Ukuran file 0.27 MB Source: repository.unj.ac.id
no reviews yet
Please Login to review.